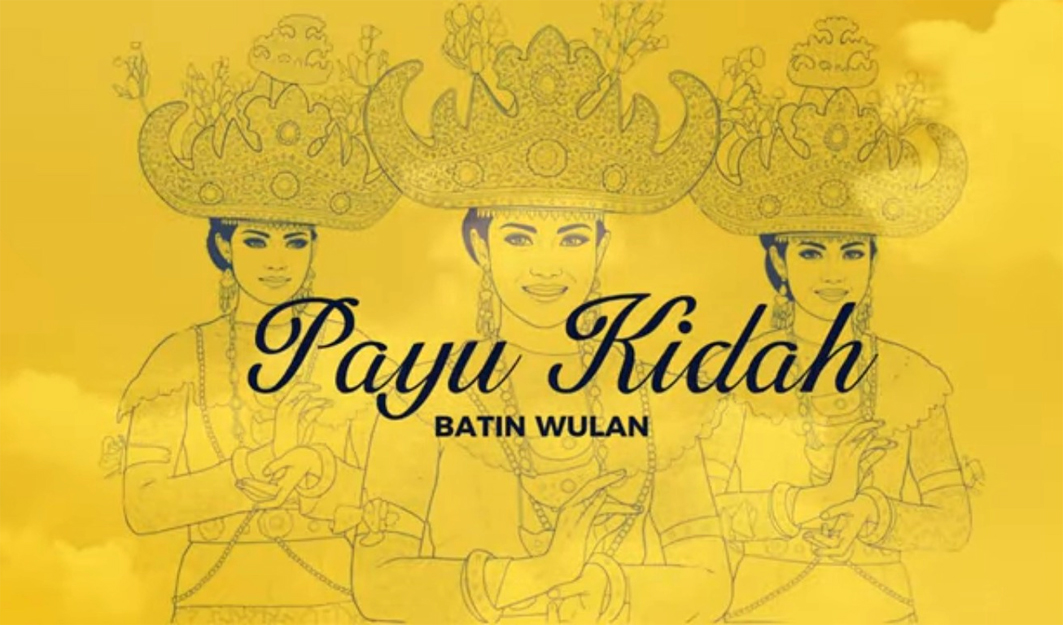Sampul lagu “Payu Kidah” (FOTO: Tangkapan Layar Sintesa Pro)
Oleh: Udo Z Karzi (Tukang tulis saja, Penerima Hadiah Sastra Rancage, tinggal di Bandar Lampung)
LAGU daerah, dalam pengertian paling mendasar, adalah ruang ekspresi kolektif sebuah masyarakat. Ia lahir bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dirasakan; bukan semata menyampaikan pesan, melainkan mengendapkan pengalaman budaya dalam bentuk bunyi, ritme, dan bahasa. Dalam konteks Lampung, lagu daerah memiliki posisi penting sebagai medium pewarisan identitas, bahasa, dan nilai-nilai lokal. Namun, perkembangan sejumlah lagu Lampung mutakhir memperlihatkan gejala yang menarik sekaligus problematis: semakin kuatnya muatan amanat pembangunan dan pelestarian adat yang justru berpotensi mengganggu pengalaman estetis pendengar. Di titik inilah muncul sebuah ungkapan yang relevan untuk membaca fenomena tersebut: ketika lagu menjadi pidato.
Fenomena ini dapat dibaca melalui lagu-lagu seperti “Cangget Agung”, “Bumi Lampung”, hingga “Payu Kidah” yang dipopulerkan oleh Batin Wulan. Lagu-lagu ini memperlihatkan kecenderungan serupa: estetika musik berjalan berdampingan dengan pesan yang sangat eksplisit, bahkan cenderung menyerupai slogan sosial. Alih-alih membiarkan pendengar tenggelam dalam rasa, lirik justru mendorong arah makna secara langsung.
Seni, Pesan, dan Beban Moral
Tidak ada yang salah ketika karya seni membawa nilai atau pesan tertentu. Sejarah musik, baik tradisional maupun modern, selalu mencatat lagu-lagu yang mengandung kritik sosial, ajakan moral, bahkan semangat perjuangan. Persoalannya muncul ketika pesan tersebut menjadi terlalu dominan sehingga menggeser posisi seni itu sendiri. Lagu bukan lagi ruang interpretasi, melainkan ruang pengarahan. Dalam konteks inilah kita bisa memahami fenomena ketika lagu menjadi pidato: seni suara kehilangan ruang lirihnya karena terlalu sibuk menjelaskan apa yang harus dilakukan pendengarnya.
Dalam “Cangget Agung”, misalnya, pendengar diajak memasuki suasana adat melalui gambaran rumah sessat, bunyi kulintang, dan ritual cangget. Secara musikal, lagu ini memiliki daya pikat karena menyentuh imaji budaya yang kuat. Namun, momentum estetis itu berubah ketika bagian akhir memasuki ajakan langsung untuk “melestarikan adat Lampung.”
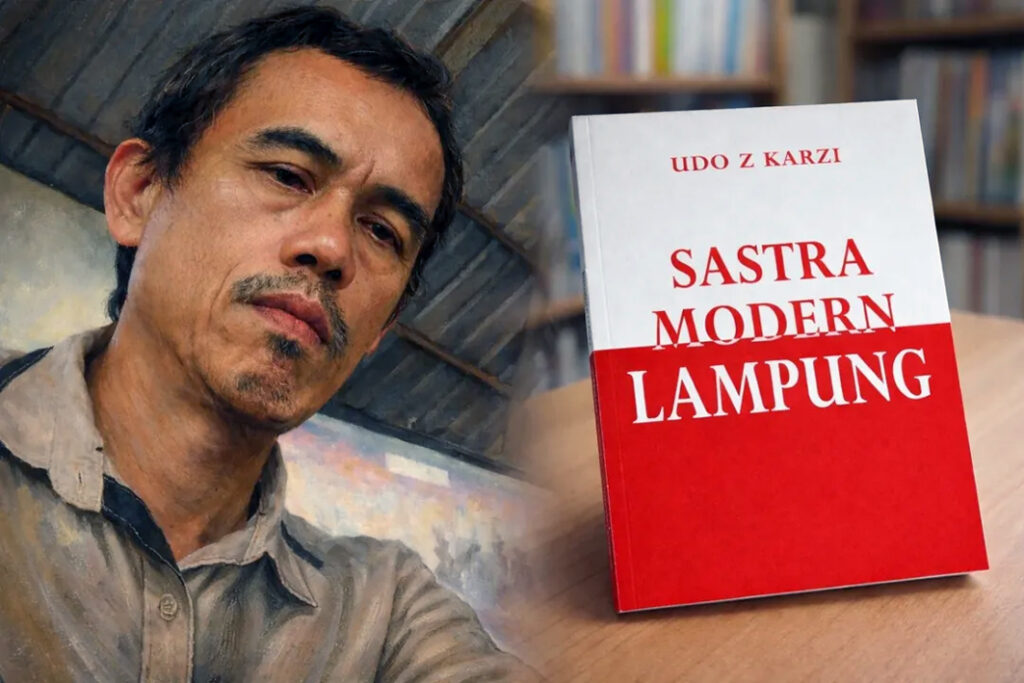
Ajakan tersebut begitu eksplisit sehingga pengalaman mendengar bergeser dari kontemplasi menjadi instruksi. Pendengar tidak lagi dibiarkan menikmati simbol budaya secara bebas, melainkan diarahkan pada kesimpulan tertentu.
Kondisi serupa tampak pada “Bumi Lampung”. Lagu ini menggambarkan kekayaan alam, keberagaman masyarakat, dan kebanggaan regional. Tetapi bahasa yang digunakan cenderung deskriptif secara literal: Lampung indah, Lampung kaya, Lampung harus dibangun bersama. Lirik tersebut terasa “kasar” dalam pengertian estetis—bukan karena bahasanya buruk, melainkan karena terlalu langsung menyatakan maksudnya. Seni biasanya bekerja melalui lapisan makna, metafora, dan ketegangan emosional; sementara lagu ini lebih menyerupai narasi informatif. Di sinilah batas antara lagu dan pidato mulai menipis.
Puncak Instrumentalisasi Budaya
Fenomena ini mencapai bentuk paling jelas dalam “Payu Kidah”. Lagu tersebut secara terang-terangan membawa agenda membangun Lampung, menjunjung bahasa daerah, serta menjalankan falsafah hidup masyarakat Lampung. Bahkan penjelasan mengenai “pesan sponsor” mempertegas fungsi lagu sebagai media kampanye nilai-nilai budaya tertentu.
Pada titik ini, lagu mengalami apa yang bisa disebut sebagai instrumentalisasi budaya—yakni ketika seni dijadikan alat untuk mencapai tujuan sosial atau simbolik tertentu. Tentu saja, niat di baliknya tidak selalu negatif. Upaya menghidupkan bahasa daerah, adat, dan filosofi lokal merupakan pekerjaan penting di tengah arus globalisasi. Namun ketika lagu terlalu menyerupai seruan resmi, daya emosionalnya justru melemah. Lagu tidak lagi mengundang, melainkan mengarahkan.
Pendengar akhirnya merasakan beban moral yang tidak kecil. Lagu yang seharusnya memberi ruang kenikmatan berubah menjadi semacam ujian loyalitas simbolik: jika menyanyikan lagu ini, berarti mendukung pelestarian budaya; jika tidak, seolah berada di posisi yang berseberangan. Inilah ironi ketika lagu menjadi pidato—ia berhenti menjadi pengalaman personal dan berubah menjadi pernyataan publik.

Estetika yang Tergusur
Secara estetis, persoalan utama dari lagu-lagu bertipe amanat ini terletak pada hilangnya ambiguitas. Dalam teori seni, ambiguitas bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Karya yang baik memberi ruang tafsir kepada pendengarnya, membiarkan makna tumbuh dari pengalaman personal masing-masing orang. Ketika lirik terlalu eksplisit, ruang itu menyempit.
Lagu-lagu daerah klasik sering kali bertahan lama justru karena tidak banyak menjelaskan. Mereka menghadirkan suasana, emosi, atau kisah yang terbuka. Pendengar bisa merasakan nostalgia, rindu, atau kebanggaan tanpa merasa sedang digurui. Sebaliknya, lagu yang penuh ajakan langsung sering kali cepat kehilangan daya tarik karena fungsi utamanya lebih bersifat pragmatis daripada artistik. Dengan kata lain, semakin dekat lagu pada gaya pidato, semakin jauh ia dari keindahan yang subtil.
Masalahnya bukan pada ajakan membangun atau melestarikan adat. Masalahnya adalah cara penyampaian yang mengorbankan substansi estetika. Seni menjadi terlalu “jelas,” sehingga kehilangan kedalaman.
Budaya sebagai Slogan
Ada kecenderungan lain yang perlu dicermati: reduksi budaya menjadi slogan-slogan normatif. Lampung digambarkan sebagai daerah indah, kaya, berbudaya, dan harus dibangun bersama. Narasi seperti ini memang menciptakan rasa bangga, tetapi sering kali mengabaikan kompleksitas realitas budaya yang sesungguhnya.
Budaya tidak hanya berisi kebanggaan; ia juga memuat konflik, perubahan, bahkan kehilangan. Ketika lagu hanya menyajikan sisi ideal dan normatif, seni kehilangan kemampuannya untuk merefleksikan kehidupan nyata. Padahal, justru melalui keraguan, kritik, dan kegelisahanlah seni menemukan kekuatan emosionalnya. Jika semua lirik berakhir pada ajakan bersama, lagu berisiko terdengar seragam dan kehilangan karakter individual.
Antara Pelestarian dan Kebebasan Artistik
Tentu tidak adil jika seluruh tanggung jawab dibebankan kepada para pencipta lagu. Dalam banyak kasus, ada dorongan sosial dan institusional yang mendorong seni menjadi alat edukasi budaya. Pemerintah daerah, komunitas budaya, bahkan publik sering mengharapkan lagu daerah menjadi media pelestarian yang efektif. Akibatnya, seniman berada di persimpangan: antara memenuhi ekspektasi sosial dan menjaga kebebasan artistik.

Di sinilah tantangan terbesar muncul. Pelestarian budaya tidak harus dilakukan melalui bahasa perintah. Lagu bisa mengajak tanpa menggurui, mengingatkan tanpa memaksa. Alih-alih berkata “mari melestarikan adat,” lagu bisa menghadirkan kisah manusia yang kehilangan identitas budaya, atau pengalaman emosional yang membuat pendengar secara alami ingin menjaga warisan tersebut.
Ketika rasa hadir lebih dahulu, pesan akan mengikuti dengan sendirinya. Seni tidak kehilangan fungsinya sebagai medium budaya, tetapi tetap menjaga martabatnya sebagai ruang kebebasan.
Mengembalikan Lagu pada Rasa
Lagu-lagu Lampung bertema pembangunan dan pelestarian adat memperlihatkan semangat kolektif yang patut dihargai. Mereka lahir dari keinginan menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Namun dari perspektif kritik seni, dominasi amanat yang terlalu eksplisit telah menggeser keseimbangan antara fungsi sosial dan pengalaman estetik.
Ungkapan “ketika lagu menjadi pidato” bukanlah tuduhan, melainkan peringatan: seni akan kehilangan daya magisnya jika terlalu sibuk mengarahkan. Lagu seharusnya membiarkan pendengar menemukan jalan emosionalnya sendiri, bukan sekadar mengikuti instruksi yang telah ditetapkan.
Jika musik Lampung ingin tetap hidup lintas generasi, tantangannya bukan hanya memperbanyak lagu tentang adat dan pembangunan, tetapi menciptakan karya yang membuat orang mencintai budaya secara tulus—tanpa merasa sedang diberi amanat. Ketika lagu kembali menjadi ruang rasa, maka pelestarian budaya tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan batin yang tumbuh alami dari pengalaman estetis itu sendiri. ●