Oleh: AI
Kota Sagara tak pernah benar-benar tidur.
Ia hanya mengganti wajahnya.
Pagi hari, ia tampak seperti perempuan renta yang bangun terlalu awal—mata sembap, napas berat, dan tubuh penuh luka yang ditutup bedak tipis bernama rutinitas. Malam hari, ia berubah menjadi binatang liar: menyeringai dengan lampu-lampu neon, mengaum lewat klakson dan teriakan manusia yang berusaha pulang atau justru melarikan diri dari rumah.
Kota itu bernama Sagara, meskipun tak ada laut di dekatnya. Nama itu diberikan oleh orang-orang lama yang percaya bahwa kota, seperti samudra, tidak pernah puas. Ia menelan apa saja, tenaga, mimpi, bahkan kenangan. Dan yang paling sering ia telan adalah anak-anaknya sendiri—pelan-pelan, tanpa suara.
Setiap pagi, Sagara batuk oleh asap. Gedung-gedungnya berdiri seperti tulang belulang raksasa yang dipoles kaca. Jalan-jalannya berdenyut oleh langkah kaki yang tergesa, seolah semua orang sedang dikejar sesuatu yang tak terlihat.
Di kota inilah Jaka Samudra belajar arti berjalan cepat tanpa tahu ke mana.
Langkahnya selalu terburu-buru, seolah waktu adalah anjing liar yang siap menggigit tumit siapa pun yang lengah. Ia bekerja di sebuah gedung kaca berlantai dua puluh enam, tempat matahari hanya boleh masuk setelah disaring tirai dan aturan. Gedung kaca itu lebih dikenal sebagai Menara Anglo. Dari luar, gedung itu tampak seperti simbol keberhasilan—dingin, tinggi, berkilau. Dari dalam, ia lebih mirip labirin tempat manusia saling berpapasan tanpa pernah benar-benar saling melihat.
Jaka memulai harinya dengan secangkir kopi pahit dan doa singkat yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Bukan karena ia tak percaya, melainkan karena ia tak ingin harapannya terdengar oleh siapa pun.
Di meja kerjanya, berkas-berkas menumpuk seperti batu nisan kecil. Setiap angka di layar komputer adalah janji dan ancaman sekaligus. Ia pandai membaca grafik, memecah laporan, dan menyusun rencana. Tapi ia tak pernah pandai membaca dirinya sendiri.
“Kerja bagus, Jaka”.
Suara itu datang dari belakang, selalu tiba tanpa aba-aba. Armand Wiratama, atasannya, berdiri dengan senyum yang tak pernah menyentuh mata. Jasnya rapi, sepatunya mengilap, dan tangannya selalu bersih—seolah tak pernah menyentuh lumpur apa pun, meski ia berdiri di atasnya.
“Terima kasih, Pak”, jawab Jaka.
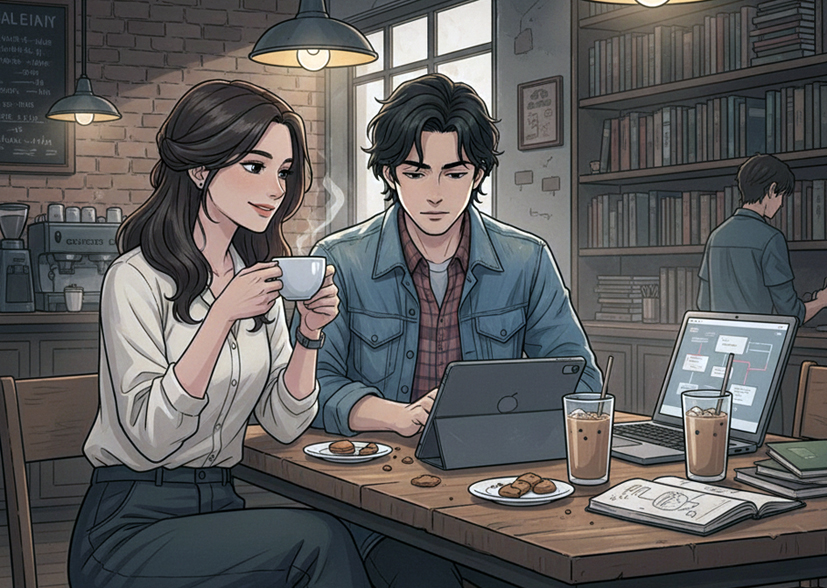
Armand mengangguk kecil. “Kita butuh orang sepertimu. Cepat, cermat, tak banyak tanya”.
Jaka tahu, pujian itu lebih mirip kontrak tak tertulis: tetap seperti ini, dan kau akan aman.
“Aman”—kata yang lama-lama terdengar seperti penjara.
* * *
Di luar gedung kaca, dunia bergerak dengan cara yang berbeda. Di warung kecil beratap seng di sudut jalan yang luput dari peta resmi, Pak Jatiswara duduk sambil menyalakan rokok linting. Rambutnya memutih lebih cepat daripada usianya, tapi matanya masih menyimpan sesuatu yang tak bisa dibeli, ketenangan.
Tidak ada yang tahu berapa usianya. Rambutnya memutih seperti abu doa yang lama terbakar. Ia tidak memakai jam, tidak juga ponsel. Waktu, katanya, hanya membuat orang terburu-buru untuk mati.
Jaka sering mampir ke warung itu sepulang kerja, meski ia tak pernah benar-benar tahu mengapa. Mungkin karena Pak Jatiswara jarang bertanya. Atau mungkin karena lelaki tua itu selalu berbicara seolah hidup adalah sungai yang harus diterima, bukan dilawan.
Di warung itu, waktu mengalir aneh. Kadang satu jam terasa seperti satu tarikan napas. Kadang satu menit seperti satu kehidupan.
Pak Jatiswara suka bercerita tentang hal-hal yang tidak tercatat: orang-orang yang hilang setelah penggusuran, sungai yang dikubur beton, dan mimpi-mimpi yang dipotong sebelum sempat tumbuh.
“Anak muda, kau kelihatan lelah”, kata Pak Jatiswara suatu malam.
“Semua orang lelah”, jawab Jaka.
Pak Jatiswara tersenyum. “Tidak semua orang sadar. Kota ini membenci orang yang bernapas terlalu lama”.
Angin malam berdesir, membawa bau aspal basah dan sisa hujan. Di kejauhan, suara sirene melolong seperti doa yang salah alamat.
“Pak,” kata Jaka tiba-tiba, “kalau kita bekerja keras, apa hidup pasti membalas?”
Pak Jatiswara menghembuskan asap. “Hidup tidak pernah berjanji membalas. Ia hanya menawarkan kemungkinan”.
“Lalu bagaimana dengan keadilan?”
“Keadilan bukan milik hidup”, jawabnya pelan. “Ia milik manusia. Dan manusia sering lupa memilikinya”.
Jaka terdiam. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergerak—seperti pintu tua yang engselnya mulai berderit.
* * *

Hujan turun tanpa aba-aba malam itu, menyapu kota seperti pengakuan yang terlambat. Jaka berlari menembus trotoar licin, dan di sanalah ia bertabrakan dengan seseorang.
“Maaf!”
Seorang perempuan berdiri di hadapannya, rambutnya basah, matanya tajam namun lelah. Ia tersenyum kecil, senyum orang yang sudah terlalu sering meminta maaf pada dunia.
“Tidak apa-apa”, katanya. “Saya juga tidak melihat”.
Namanya Laras Kirana. Seorang jurnalis lepas yang hidupnya diisi catatan, rekaman, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak disukai banyak orang.
Mereka bertemu lagi. Dan lagi.
Di kafe kecil yang lampunya redup, Laras bercerita tentang lapisan-lapisan kota yang tak pernah masuk laporan resmi. Tentang buruh yang dihapus namanya, tentang proyek yang memakan kampung, tentang data yang disulap menjadi cerita indah.
“Kau bekerja di dalam sistem”, kata Laras suatu malam. “Apa kau pernah bertanya untuk siapa sistem itu dibuat?”
Pertanyaan itu menghantam Jaka lebih keras daripada kritik mana pun di kantor.
“Aku hanya menjalankan pekerjaanku”, jawabnya.
“Semua orang begitu,” kata Laras. “Itulah masalahnya”.
Sejak malam itu, tidur Jaka tak pernah nyenyak. Angka-angka di kepalanya berubah menjadi wajah. Grafik naik-turun berubah menjadi jerit yang tertahan.
* * *

Jaka mulai melihat hal-hal yang dulu ia abaikan: laporan yang dimanipulasi, keputusan yang menyingkirkan banyak orang demi segelintir keuntungan. Ia tahu jika ia bicara, ia akan jatuh. Jika diam, ia akan ikut bersalah.
Armand menawarkan promosi.
“Ini kesempatanmu”, kata Armand. “Jangan rusak masa depanmu dengan idealisme murahan”.
Laras menemukan bukti.
“Jika ini keluar”, katanya, “Banyak orang akan kehilangan kekuasaan. Termasuk atasanmu”.
Jaka berdiri di persimpangan yang tak tertulis di peta mana pun.
* * *
Jaka mengingat Pak Jatiswara, yang suatu hari menghilang tanpa kabar. Warungnya tutup. Katanya, digusur dini hari. Tak ada laporan. Tak ada berita. Sengnya hilang. Tak ada bekas perlawanan. Seolah ia tak pernah ada.
“Dia menghilang”, kata Laras pelan.
Jaka merasa perutnya kosong. Seperti ada bagian kota yang dicabut paksa dari dadanya.
Jaka memilih.
Bukan dengan cara heroik. Bukan dengan teriak atau pidato. Ia memilih dengan mengirim data—diam-diam, malam-malam, dengan tangan gemetar.
Malam itu, ia mengirimkan semua data ke Laras. Tangannya gemetar. Layar berkedip. Di pantulan kaca, wajahnya tampak asing.
Ia menekan tombol “Enter”.
Dan Sagara menahan napas.
Konsekuensinya datang cepat.
Ia dipecat. Namanya dicoret. Teleponnya sunyi.
Laras menerbitkan laporan itu. Kota gaduh. Tapi seperti biasa, gaduh tak selalu berarti berubah.
Sagara berubah.
Malam itu lampu-lampu jalan berkedip lebih lama. Hujan turun tanpa pola. Orang-orang bermimpi hal yang sama, bangunan runtuh dari dalam, tanpa suara.
Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tanpa nama melompat dari Menara Anglo. Tak ada berita besar. Hanya catatan singkat di pojok halaman. “Jalan Ditutup Sementara”.
Malamnya, hujan turun lagi.
Di warung kecil yang tiba-tiba muncul kembali di sudut jalan, secangkir kopi mengepul sendirian. Tidak ada penjual. Tidak ada pembeli.
* * *
Jaka kembali berjalan kaki. Lebih lambat kali ini. Ia tak lagi mengejar apa pun. Ia belajar berdiri.
Di reruntuhan hidup lamanya, ia menemukan sesuatu yang lebih sunyi: kejujuran.
Ia membuka kafe kecil bersama Laras, tempat orang-orang bisa berbagi cerita. Tak besar. Tak megah. Tapi nyata.
Kota Sagara tetap lapar.
Ia mungkin tak akan pernah kenyang.
Tapi di sudut kecilnya, ada cahaya yang tidak menyilaukan—cahaya yang cukup untuk melihat wajah sendiri di cermin, tanpa harus menunduk.
Dan bagi Jaka, itu sudah lebih dari cukup.
Tamat
Penyusun: Maspril Aries






