KINGDOMSRIWIJAYA – Dalam sebuah obrolan dengan beberapa wartawan di sebuah kedai kopi tidak bersuasana milenial di tengah kota ini, seorang wartawan menarik kesimpulan, “Kondisi pers selama tahun 2025 sedang tidak baik-baik saja”.
Kesimpulan itu di-“Amiinkan” oleh yang lain. Walau sempat terjadi diskusi sempalan yang mencoba membantah kesimpulan itu. Namun ternyata argumentasinya dapat dimentahkan, apa lagi dipaparkan dengan melihat yang terjadi terhadap pers pada waktu menjelang tutup tahun 2025.
Jika kesimpulan tersebut benar adanya, kondisi pers sedang tidak baik-baik saja. Maka kesimpulan itu mengingatkan pada sebuah liputan majalah Time tahun 1983. Time terbit dengan cover story berjudul “Journalism Under Fire”. Dalam edisi yang terbit 12 Desember 1983 tersebut, Time menerbitkan feature panjang berjudul “Journalism Under Fire” yang ditulis William A. Henry III.
Majalah Time edisi “Journalism Under Fire” adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan situasi pers yang menghadapi serangan—baik kritik publik, skandal internal, maupun tekanan hukum dan fisik. Kemudian frasa tersebut juga dipakai dalam kajian dan buku yang membahas ancaman terhadap jurnalisme investigatif dan kebebasan pers
Artikel William A. Henry menempatkan fenomena tersebut sebagai masalah struktural, selain kritik eksternal, pers juga sedang menghadapi masalah internal seperti kasus-kasus fabrikasi dan pembengkakan ego redaksional yang memicu kemarahan publik. Time mengaitkannya dengan penurunan kepercayaan dengan beberapa skandal jurnalistik awal 1980-an yang membuat pembaca meragukan kredibilitas media besar seperti Time.
Sebelum membahas lebih dalam tentang Journalism Under Fire, mari mengenal William A. Henry III. Ia adalah seorang kritikus budaya dan jurnalis Amerika Serikat yang menulis cover story “Journalism Under Fire”. Henry yang meninggal 28 Juni 1994 dikenal sebagai penulis produktif, pemenang penghargaan, dan pengamat tajam soal media dan budaya populer. Selain sebagai kritikus budaya, penulis feature untuk Time ia juga kolumnis/penulis untuk beberapa media besar Amerika.
Karier jurnalistik Henry dimulai di The Boston Globe, ia menulis liputan dan kritik budaya; liputannya tentang desegregasi sekolah di Boston mendapat perhatian luas dan menjadi bagian dari reputasinya sebagai jurnalis investigatif dan kritikus tajam. Henry juga meraih penghargaan bergengsi dalam jurnalisme—termasuk pengakuan untuk karya-karya kritik televisi dan liputan—yang menegaskan reputasinya sebagai salah satu kritikus budaya terkemuka pada masanya. Pada awal 1980‑an Henry menjadi salah satu penulis tetap Time yang menulis feature panjang dan esai budaya.

Pengertian dan konteks istilah
Selanjutnya mari mendiskusikan tentang Journalism Under Fire. Istilah yang bermula diperkenalkan majalah Time tersebut pada dasarnya merangkum kondisi di mana media massa menjadi sasaran kritik, delegitimasi, dan ancaman—mulai dari tuduhan bias dan ketidakakuratan hingga intimidasi hukum dan kekerasan fisik. Time menggunakan frasa ini sebagai judul cover story besar yang menelaah krisis kepercayaan publik terhadap pers Amerika pada awal 1980-an. Ketika itu opini publik mulai memandang wartawan sebagai arogan, partisan, dan tidak akurat
Frasa itu kemudian meluas menjadi tema kajian akademis dan buku. Misalnya, Stephen Gillers menulis buku berjudul Journalism Under Fire: Protecting the Future of Investigative Reporting yang membahas ancaman hukum dan finansial terhadap jurnalisme investigatif—bagaimana gugatan, tekanan korporat, dan perubahan filosofi yudisial dapat mengikis kemampuan media untuk melakukan pengawasan publik yang efektif. Kajian akademis lain juga menggunakan istilah serupa untuk menelaah bagaimana jurnalis menghadapi tekanan politik, ekonomi, dan keamanan dalam praktik sehari-hari.
Jurnalisme bukan sekadar profesi yang mencatat peristiwa; ia adalah mekanisme pengawasan publik, ruang pembentukan opini, dan sarana penegakan akuntabilitas. Ketika jurnalisme berada dalam kondisi tertekan—dihantam retorika delegitimasi, dibatasi oleh aturan hukum yang multi tafsir, diintimidasi secara fisik, atau diserang di ranah digital—kita menyebutnya sebagai journalism under fire. Fenomena ini bukan sekadar istilah retoris: ia menggambarkan realitas yang memengaruhi kemampuan media untuk menjalankan fungsi publiknya.
Journalism under fire adalah cermin dari kondisi politik, sosial, dan teknologi suatu masyarakat. Ketika jurnalisme diserang—baik melalui undang-undang yang represif, tekanan ekonomi, kekerasan fisik, maupun serangan digital—demokrasi kehilangan salah satu pilar pentingnya: kemampuan publik untuk memperoleh informasi yang akurat dan menuntut akuntabilitas.
Journalism Under Fire adalah kondisi di mana jurnalisme menghadapi serangan sistemik—retorika delegitimasi, tekanan hukum, ancaman fisik, dan serangan digital—fenomena yang berakar historis dan tetap nyata di era digital; di Indonesia bentuknya meliputi pembredelan masa Orde Baru, kriminalisasi lewat UU ITE, intimidasi lapangan, dan pembubaran acara publik.
Journalism under fire bukan sekadar masalah profesi; ia adalah masalah demokrasi. Melindungi jurnalisme berarti melindungi hak publik untuk mengetahui, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Di era di mana informasi dapat menjadi senjata sekaligus obat, menjaga kebebasan pers adalah tugas bersama yang menentukan kualitas masa depan publik kita.

Historis dan konsep
Jika mau menyimak ke belakang, bahwa kontrol atas kata-kata dan teks adalah praktik politik kuno: peristiwa yang sering dikutip sebagai contoh awal adalah pembakaran buku pada masa Dinasti Qin, yang dimaknai sebagai upaya menyatukan ideologi negara
Di Eropa, Gereja Katolik menginstitusikan Index Librorum Prohibitorum sebagai daftar buku terlarang untuk menjaga doktrin dan moral publik. Pada abad ke‑20 ada kampanye pembersihan budaya seperti pembakaran buku Nazi (10 Mei 1933) menunjukkan bagaimana sensor bisa menjadi alat politik untuk menghapus pluralitas intelektual.
Semua ini menegaskan bahwa ancaman terhadap jurnalisme dan wacana bukan fenomena baru, melainkan evolusi dari kontrol wacana tradisional menuju bentuk modern yang lebih beragam.
Mengapa jurnalisme “under fire”? Jurnalisme itu dipandang mengancam kekuasaan karena ia mengungkap fakta, membentuk opini publik, dan menuntut akuntabilitas. Ketika aktor politik atau ekonomi merasa terancam, mereka menggunakan retorika delegitimasi, gugatan hukum, tekanan ekonomi, dan kadang kekerasan untuk melemahkan media.
Mari bayangkan bagaimana journalism under fire itu masuk ke ruang news room media massa. Bayangkan seperti ini, ada seorang editor senior media online menatap layar komputernya dengan perasaan campur aduk. Sebuah laporan investigasi tentang aliran dana sebuah proyek strategis nasional hampir rampung. Namun, telepon dari seorang “tokoh” beberapa jam sebelumnya masih terngiang. Bukan ancaman kasar, tetapi sindiran halus tentang “stabilitas” dan “kepentingan bangsa”.
Sementara itu, di timeline media sosial, buzzer politik sudah mulai menyebarkan narasi bahwa medianya anti-pembangunan. Di era di mana informasi mengalir deras, justru tekanan terhadap jurnalisme tidak hilang; ia berubah wajah, menjadi lebih multifaset, sistemik, dan halus. Inilah wujud kontemporer dari fenomena abadi journalism under fire.
Journalism Under Fire bukan sekadar metafora dramatis. Ia adalah kondisi nyata di mana praktik jurnalisme yang ideal—berdasarkan prinsip akurasi, independensi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada publik—menghadapi tekanan, ancaman, pembatasan, dan upaya pelemahan dari berbagai aktor kekuasaan, baik politik, ekonomi, agama, maupun sosial.
Di era milenial, ancaman meluas, disinformasi terorganisir, pelecehan daring, dan moderasi platform yang tidak konsisten menambah lapisan risiko. Laporan UNESCO menunjukkan penurunan kebebasan berekspresi global dan lonjakan self‑censorship, serta peningkatan ancaman terhadap keselamatan jurnalis dalam beberapa tahun terakhir.

Kemerdekaan Pers
Apakah journalism under fire sama dengan pembatasan kemerdekaan pers? Pertanyaan ini mendasar. Jawabannya adalah: ya, tetapi tidak sesederhana itu. Keduanya saling terkait erat, namun memiliki nuansa berbeda. Kemerdekaan pers (freedom of the press) adalah prinsip normatif dan kerangka hukum yang menjamin hak media untuk beroperasi tanpa campur tangan negara yang sewenang-wenang. Ia diatur dalam konstitusi, UU, dan standar HAM internasional (seperti Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Journalism under fire adalah kondisi empiris dan operasional yang dialami oleh praktisi dan institusi pers ketika mereka mencoba menjalankan peran idealnya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh pelanggaran terhadap kemerdekaan pers (misalnya, sensor, kekerasan negara), tetapi juga oleh faktor-faktor di luar negara yang sama berbahayanya.
Dengan kata lain, setiap pembatasan kemerdekaan pers yang sistemik akan menyebabkan journalism under fire. Namun, journalism under fire bisa terjadi bahkan di negara dengan jaminan kemerdekaan pers di atas kertas, jika tekanan berasal dari aktor non-negara (preman, korporasi, kelompok agama ekstrem, masyarakat digital) dan negara lalai dalam memberikan perlindungan (failure to protect).
Keterkaitannya adalah saling memperkuat, dimana pembatasan formal memperparah kondisi under fire, sementara delegitimasi dan ancaman non-formal juga mengurangi kebebasan praktis pers. Untuk melindungi jurnalisme, kebijakan harus menangani kedua dimensi ini.
Sementara perbedaan antara keduanya, journalism under fire adalah kondisi empiris: jurnalis diserang, diintimidasi, atau dipaksa melakukan self‑censorship. Pembatasan kemerdekaan atau kebebasan pers adalah tindakan hukum atau kebijakan yang membatasi hak pers (sensor, larangan, undang‑undang represif).
Atau dengan kata lain, pembatasan kebebasan pers adalah alat atau kebijakan yang digunakan (terutama oleh negara), sedangkan “journalism under fire” adalah kondisi atau pengalaman yang dialami jurnalis dan media akibat berbagai ancaman, termasuk penggunaan alat pembatasan kebebasan pers tersebut. Sebuah negara bisa memiliki undang-undang pers yang relatif bebas (pembatasan minimal), tetapi jurnalisnya tetap “under fire” karena ancaman dari kelompok kriminal, perusahaan rakus, atau kampanye disinformasi digital yang masif.
Jika merujuk Teori Tanggung Jawab Sosial yang memperluas konsep kebebasan dengan menekankan bahwa pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam praktiknya, klaim “tanggung jawab sosial” sering disalahgunakan oleh penguasa untuk membatasi pemberitaan kritis. Di sinilah letak ketegangan abadi: ketika jurnalisme melakukan peran watchdog-nya, ia akan selalu berisiko “terbakar”, baik oleh hukum yang represif maupun oleh reaksi sosial yang keras.
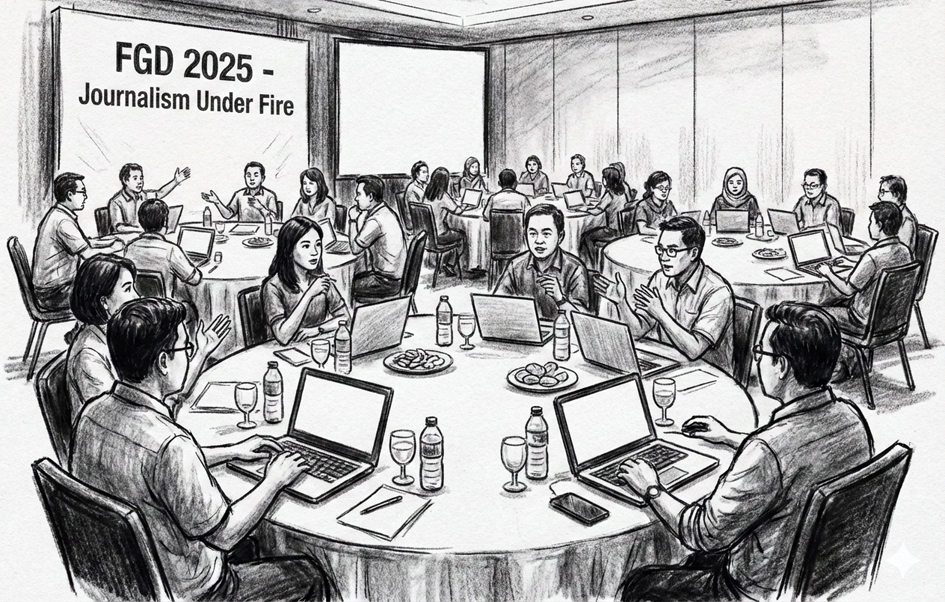
Berikut beberapa bentuk ancaman terhadap jurnalisme saat ini yang bersifat multidimensi. Klasifikasi pertama, retorika delegitimasi dan disinformasi. Dilakukan dengan kampanye yang menuduh media menyebarkan kebohongan atau berpihak, sering disertai penyebaran informasi palsu yang menenggelamkan fakta. Dampaknya, erosi kepercayaan publik; kesulitan verifikasi; tekanan psikologis pada jurnalis.
Klasifikasi kedua, tekanan hukum dan kriminalisasi. Prakteknya dengan penggunaan pasal pidana, gugatan perdata, atau undang‑undang multitafsir untuk menjerat peliput. Dampak yang ditimbulkan risiko finansial dan hukum bagi media; chilling effect; pengurangan liputan investigatif.
Klasisifikasi ketiga, rekanan ekonomi dan kepemilikan media. Bentuknya, pemutusan iklan, tekanan pemilik modal, dan konsolidasi media yang mengurangi pluralitas. Dengan dampaknya pengaruh kepentingan ekonomi terhadap editorial; pengurangan sumber daya untuk jurnalisme mendalam.
Klasifikasi keempat, ancaman fisik dan kekerasan. Prakteknya terjadi intimidasi, penganiayaan, penculikan, hingga pembunuhan jurnalis. Dampaknya, risiko keselamatan nyata; impunitas memperkuat ancaman; penurunan liputan isu sensitif.
Klasifikasi kelima, serangan digital dan pelecehan daring. Bentuknya, doxxing, kampanye pelecehan terkoordinasi, serangan siber terhadap infrastruktur media. Dampaknya, gangguan operasional; tekanan psikologis; pembatasan partisipasi jurnalis, terutama perempuan dan minoritas.
Klasifikasi keenam, tekanan administratif dan pembatasan acara publik. Seperti penolakan izin, pembubaran diskusi, dan intervensi aparat lokal dengan dalih prosedural atau keamanan, yang berdampak pada penutupan ruang dialog publik; pembatasan penyebaran gagasan.
Oleh karena itu, membela jurnalisme yang under fire adalah inti dari mempertahankan kemerdekaan pers yang substantif, bukan hanya formal. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yakni praksis kebebasan.
Untuk mengatasi tantangan tersebut memerlukan pendekatan holistik mencakup reformasi hukum, perlindungan keselamatan, penguatan institusi media, literasi publik, dan tanggung jawab platform teknologi. Jangan dilupakan, juga dibutuhkan komitmen kolektif—dari negara, masyarakat sipil, komunitas jurnalis, dan sektor swasta—untuk mempertahankan ruang publik yang memungkinkan kata-kata, fakta, dan kritik berkembang tanpa takut.
Jadi journalism under fire bukan sekadar masalah profesi, ia adalah masalah demokrasi. Melindungi jurnalisme berarti melindungi hak publik untuk mengetahui, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Di era di mana informasi dapat menjadi senjata sekaligus obat, menjaga kebebasan pers adalah tugas bersama yang menentukan kualitas masa depan publik kita.
Perjalanan panjang “Journalism Under Fire” – dari mesin cetak yang dibredel hingga algoritma yang dimanipulasi – menunjukkan bahwa pertarungan untuk kebebasan menyuarakan kebenaran adalah pertarungan abadi. (maspril aries)






