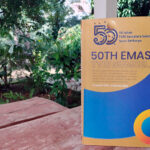KINGDOMSRIWIJAYA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa, 13 Januari 2026 akan menggelar Diskusi Publik dengan mengusung tema “Krisis Iklim & Petaka Ekologis di Indonesia”. Diskusi menghadirkan nara sumber yang berkompeten di bidangnya. Ada Boy Jerry Even Sembiring Direktur Eksektif Walhi, Pantoro Tri Kuswardono Direktur Yayasan Pikul, Lasma Natalia Panjaitan Direktur Eksekutif ICEL, dan Reynado Sembiring dari STH Jentera.
Diskusi publik ini menjadi relevan ketika berlangsung pasca terjadinya bencana ekologis yang melanda Sumatera, terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Selain penanggulangan bencana sudah banyak pembahasan dan diskusi yang membahas bencana ekologis tersebut. Mari tidak lagi menggunakan diksi “bencana alam” terhadap bencana yang terjadi di tiga daerah tersebut.
Walhi Sumsel melihat apa yang terjadi di tiga provinsi tersebut dan juga di daerah lainnya di Indonesia sebagai “petaka ekologis”. Diksi ini diplih tentunya bukan tanpa alasan. Ada istilah “bencana alam, bencana ekologis” dan “petaka ekologis” yang perlu dikenali dan diketahui jika membahas tentang apa yang terjadi di Sumatera pada Desember 2025.
Mari fahami bahwa fenomena bencana merupakan bagian integral dari sejarah manusia dan lingkungan. Dalam literatur akademis, istilah “bencana alam”, “bencana ekologis”, dan “petaka ekologis” sering digunakan, namun masing-masing memiliki nuansa konseptual yang berbeda. Penjelasan yang argumentatif diperlukan agar kita tidak sekadar menyamakan semua peristiwa destruktif sebagai “bencana alam”, padahal banyak di antaranya merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor alam, sosial, dan ekologis.
Bencana Alam adalah peristiwa destruktif yang terjadi akibat fenomena geofisik atau meteorologis tanpa keterlibatan langsung aktivitas manusia. Contoh klasik: gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, badai tropis. Karakteristiknya, berasal dari dinamika alam (tektonik, vulkanik, hidrometeorologi). Tidak selalu dapat diprediksi, meski teknologi mitigasi semakin maju. Dampaknya diperparah oleh kerentanan sosial (misalnya pemukiman di zona rawan). Contohnya gempa bumi dan tsunami Aceh 2004.
Bencana Ekologis, definisinya adalah, peristiwa destruktif yang terjadi akibat kerusakan ekosistem, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Karakteristiknya melibatkan degradasi lingkungan (deforestasi, pencemaran, hilangnya biodiversitas). Berdampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekologi. Seringkali merupakan hasil interaksi antara faktor alam dan antropogenik. Contoh kebakaran hutan dan di Sumatera dan Kalimantan, pencemaran sungai akibat limbah industri, kerusakan terumbu karang.

Petaka Ekologis adalah istilah yang lebih normatif dan filosofis, merujuk pada kehancuran ekosistem yang bersifat katastropik, mengancam keberlanjutan hidup manusia dan makhluk lain. Karakteristiknya, tidak hanya bencana sesaat, tetapi krisis ekologis yang sistemik. Mengguncang fondasi kehidupan (air, pangan, udara). Biasanya terkait dengan krisis iklim, kapitalisme ekstraktif, dan kegagalan tata kelola lingkungan. Contohnya, hilangnya hutan hujan tropis Amazon, pencairan es di Kutub, krisis iklim global yang memicu banjir dan kekeringan ekstrem. Dan menurut Walhi Sumsel apa yang terjadi di Sumatera adalah petaka ekologis.
Apa itu kehancuran ekosistem yang bersifat katastropik? Kehancuran ekosistem yang bersifat katastropik adalah kondisi ketika suatu ekosistem mengalami kerusakan mendalam, luas, dan mendadak sehingga fungsi-fungsi ekologis utamanya tidak lagi berjalan. Kata katastropik sendiri merujuk pada sesuatu yang bersifat bencana besar, dramatis, dan sulit dipulihkan.
Ciri-ciri kehancuran ekosistem katastropik terjadi dalam skala luas, berupa kerusakan terjadi pada area yang sangat besar, misalnya hutan hujan tropis, terumbu karang, atau lapisan es kutub. Cepat dan mendadak, perubahan terjadi dalam waktu relatif singkat, sehingga organisme tidak sempat beradaptasi. Fungsi ekologi lumpuh, siklus air, siklus karbon, atau rantai makanan terganggu sehingga ekosistem tidak lagi menopang kehidupan. Dan sulit dipulihkan, meski ada upaya restorasi, kerusakan bersifat permanen atau membutuhkan waktu ratusan tahun untuk kembali stabil.
Di Indonesia terjadi pada petaka kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran lahan gambut yang luas tidak hanya merusak ekosistem lokal, tetapi juga menimbulkan krisis kesehatan lintas negara. Implikasi Kehancuran ekosistem katastropik bukan sekadar “bencana alam” biasa, melainkan petaka ekologis karena dampaknya sistemik, mengganggu keseimbangan iklim global. Mengancam keberlanjutan pangan dan air. Menyebabkan hilangnya biodiversitas secara massal. Memicu krisis sosial-ekonomi (migrasi, konflik sumber daya).
Dengan kata lain, kehancuran ekosistem katastropik adalah titik balik di mana alam kehilangan kemampuan untuk menopang kehidupan manusia dan makhluk lain secara berkelanjutan.
Krisis Iklim
Tiga diksi tersebut (bencana alam, bencana ekologis dan petaka ekologis) dalam setiap peristiwa yang terjadi selalu bertali-temali dengan perubahan iklim atau krisis iklim. Perubahan iklim saat ini tidak lagi dapat dipahami sebagai fenomena lingkungan semata. Ia telah menjelma menjadi krisis multidimensional yang mengancam fondasi peradaban manusia: pangan, air, kesehatan, ekonomi, stabilitas sosial, hingga legitimasi negara.

Sebuah Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Keenam (AR6) dalam menyebutkan, bahwa perubahan iklim telah menyebabkan dampak yang meluas, cepat, dan semakin intens di seluruh dunia, dengan negara-negara berkembang sebagai pihak yang paling rentan meski kontribusi emisinya relatif kecil.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan biodiversitas dan sumber daya alam yang melimpah, berada di episentrum krisis iklim global. Ironisnya, kekayaan alam tersebut justru menjadi sumber petaka ekologis akibat model pembangunan ekstraktif yang bertumpu pada eksploitasi hutan, tambang, dan perkebunan skala besar. Krisis iklim di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan krisis ekologis, ketimpangan sosial, konflik agraria, dan lemahnya tata kelola sumber daya alam.
Banjir dan longsor yang berulang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, juga daerah lain di Sumatera termasuk Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir bukanlah anomali alam, melainkan konsekuensi logis dari rusaknya bentang alam akibat deforestasi masif, degradasi daerah aliran sungai (DAS), serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Fenomena ini memperkuat tesis bahwa krisis iklim bukan sekadar persoalan cuaca ekstrem, tetapi manifestasi dari krisis tata kelola dan ketidakadilan struktural.
Peradaban Manusia
Dengan terjadinya petaka ekologis di muka bumi, peradaban manusia saat ini sedang berdiri di persimpangan jalan yang paling menentukan dalam sejarah eksistensinya. Krisis iklim bukan lagi sekadar prediksi saintifik tentang masa depan yang jauh, melainkan realitas objektif yang sedang merobek tatanan sosial, ekonomi, dan ekologis di seluruh penjuru bumi. Fenomena pemanasan global yang dipicu oleh akumulasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer telah melampaui ambang batas alamiahnya, memicu rangkaian bencana yang saling berkelindan—apa yang kita sebut sebagai “Petaka Ekologis.
Bagi Indonesia, krisis iklim bukan hanya ancaman terhadap lingkungan hidup, melainkan ancaman eksistensial terhadap keberlangsungan peradaban. Ketika sawah-sawah petani terendam banjir dan rob, ketika nelayan kehilangan arah karena pola angin yang tak menentu, dan ketika masyarakat adat kehilangan hutan sebagai ruang hidupnya, di situlah fondasi kebangsaan kita sedang digerogoti.
Laporan IPCC Keenam (AR6) telah memberikan “Kode Merah bagi Kemanusiaan”. Dunia telah memanas sekitar 1,1°C dibandingkan masa pra-industri. Jika tren emisi saat ini berlanjut, ambang batas kritis 1,5°C akan terlampaui dalam satu dekade ke depan. Dampaknya adalah umpan balik positif (positive feedback loops) yang tidak dapat diubah, seperti mencairnya permafrost dan hilangnya lapisan es kutub.
Secara global, krisis iklim didorong oleh model ekonomi ekstraktif yang bergantung pada bahan bakar fosil. Transisi energi menjadi agenda utama dalam setiap pertemuan COP (Conference of the Parties). Namun, transisi ini menghadapi tantangan besar, bagaimana beralih ke energi terbarukan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan tanpa menciptakan ketidakadilan baru (misalnya, eksploitasi nikel untuk baterai EV yang justru merusak hutan).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan pemilik hutan tropis serta lahan gambut terluas. Posisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai “benteng terakhir” iklim global, namun sekaligus wilayah yang paling rentan.
Banjir di Sumatera dengan gelondongan kayu yang berserakan bagian dari rangkaian fakta bahwa laju deforestasi di Indonesia, meski diklaim menurun dalam beberapa tahun terakhir, tetap berada pada level yang mengkhawatirkan bagi stabilitas ekologis. Berdasarkan data pemantauan hutan, konversi hutan menjadi perkebunan monokultur skala besar (sawit), pertambangan batu bara, dan proyek strategis nasional lainnya menjadi penyumbang utama emisi karbon Indonesia.
Kasus Sumatera Selatan
Bentang alam Provinsi Sumatera Selatan adalah sebuah anugerah yang terluka. Sumatera Selatan memiliki karakteristik geografis yang unik, membentang seluas 87.017,41 km². Di bagian barat, berdiri megah Bukit Barisan sebagai “Menara Air” yang menyuplai kehidupan bagi sungai-sungai besar, terutama Sungai Musi dan anak-anak sungainya (Ogan, Komering, Lematang, dll.). Di bagian timur, terhampar lahan basah dan gambut yang luas.
Namun, bentang alam ini kini berada dalam kondisi kritis. Eksploitasi sumber daya alam skala besar telah mengubah wajah Sumatera Selatan. Di kawasan hulu aktivitas pertambangan batubara dan pembukaan lahan untuk perkebunan di lereng-lereng Bukit Barisan telah menghilangkan vegetasi penahan air. Akibatnya, stabilitas tanah goyah.
Di kawasan hilir, drainase lahan gambut untuk konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) dan sawit telah menyebabkan penurunan muka tanah (subsidence) dan membuat wilayah ini menjadi sangat rentan terbakar saat kemarau.
Data Walhi Sumatera Selatan periode 2024-2025 menjadi alarm keras. Ada 158 kejadian banjir dan 48 peristiwa tanah longsor. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari ribuan keluarga yang kehilangan harta benda, akses pendidikan yang terputus, dan ancaman kesehatan.
Sumatera Selatan kini terjebak dalam siklus “Bencana Dua Musim”. Musim hujan, air kiriman dari hulu yang gundul meluap ke sungai-sungai yang telah mengalami sedimentasi parah, menenggelamkan pemukiman di hilir dan perkotaan (termasuk Palembang). Musim kemarau membuat lahan gambut yang telah dikeringkan melalui kanal-kanal perusahaan menjadi bahan bakar yang mudah tersulut, menciptakan bencana kabut asap (Karhutla) yang berdampak pada kesehatan lintas batas, lintas negara.
Apakah kita mau mengakui bahwa ketidakseimbangan ini membuktikan bahwa kerusakan ekologi di Sumatera Selatan telah mencapai titik jenuh? Pembangunan yang mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi justru menghasilkan biaya sosial dan ekologis (externalities) yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapat.

UU Keadilan Iklim
Terhadap apa yang terjadi di Indonesia selain membutuhkan agenda solusi dan aksi konkret untuk menyelamatkan peradaban bangsa dari petaka ekologis, diperlukan langkah-langkah radikal dan sistematis. Seperti moratorium permanen dan evaluasi izin, transisi energi yang berkeadilan (Just Energy Transition), restorasi ekosistem berbasis masyarakat seperti pemulihan DAS Musi dan restorasi gambut di Sumatera Selatan harus melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama, bukan sekadar objek.
Kemudian dibutuhkan pengarusutamaan adaptasi iklim dalam perencanaan daerah. Setiap kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus melalui “climate proofing” atau uji ketahanan iklim. Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan proyeksi kenaikan air laut dan intensitas hujan ekstrem. Perlu diselenggarakan pendidikan dan kesadaran ekologis dengan membangun kesadaran kolektif melalui pendidikan formal dan informal. Krisis iklim harus menjadi kurikulum wajib untuk menumbuhkan etika lingkungan pada generasi mendatang.
Yang tidak boleh dilupakan dan sering terlupakan, juga dibutuhkan payung hukum yang komprehensif. Selama ini, narasi yang berkembang adalah “Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim”. Namun, istilah ini seringkali bersifat netral dan gagal menangkap aspek ketidakadilan sistemik. Keadilan iklim (Climate Justice) mengakui bahwa mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi (petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat) adalah mereka yang paling menderita akibat dampaknya.
Saat ini dan ke depan, Indonesia perlu melakukan reformasi hukum lingkungan, butuh UU Keadilan Iklim sebagai framework law yang mengintegrasikan prinsip keadilan iklim ke dalam seluruh kebijakan nasional, mencakup mitigasi, adaptasi, loss and damage, serta penegakan hukum terhadap pelaku emisi tinggi.
UU Keadilan Iklim Berbeda dengan UU No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup yang lebih fokus pada aspek teknis seperti Amdal, UU Keadilan Iklim ini menekankan ketimpangan struktural, hak masyarakat rentan, dan penghentian aktivitas ekstraktif seperti deforestasi. Prinsip utamanya meliputi keadilan sosial, gender, partisipasi bermakna, dan sanksi administratif-perdata bagi perusahaan penyebab krisis iklim.
Berbagai stakeholder, komunitas yang peduli lingkungan dan aktivis lingkungan kini terus mendorong rancangan undang-undang (RUU) Keadilan Iklim ini. RUU Keadilan Iklim diusulkan oleh masyarakat sipil melalui Koalisi untuk Keadilan Iklim (Walhi, ICEL, Yayasan Pikul) sejak 2023, yang mendesak DPR memasukkannya ke Prolegnas. Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) telah meluncurkan Naskah Akademik dari RUU ini pada Agustus 2025.
Kajian yuridis normatif menunjukkan reformasi hukum lingkungan diperlukan karena regulasi saat ini fragmentaris, lemah penegakan, dan minim adaptasi. Undang-Undang Keadilan Iklim bukan sekadar instrumen hukum, melainkan komitmen moral dan politik untuk melindungi generasi hari ini dan masa depan. Pilihannya jelas: melanjutkan jalan destruktif atau membangun masa depan yang adil, lestari, dan berdaulat secara ekologis.
Sebagai penutup, harus melekat dalam ingatan bangsa ini bahwa krisis iklim dan petaka ekologis adalah ujian terbesar bagi peradaban manusia dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Tanpa perubahan paradigma pembangunan dan keberanian politik untuk menempatkan keadilan ekologis sebagai fondasi kebijakan, krisis ini akan terus berulang dan semakin menghancurkan. (maspril aries)
#Penulisan konten ini diolah dengan bantuan AI.